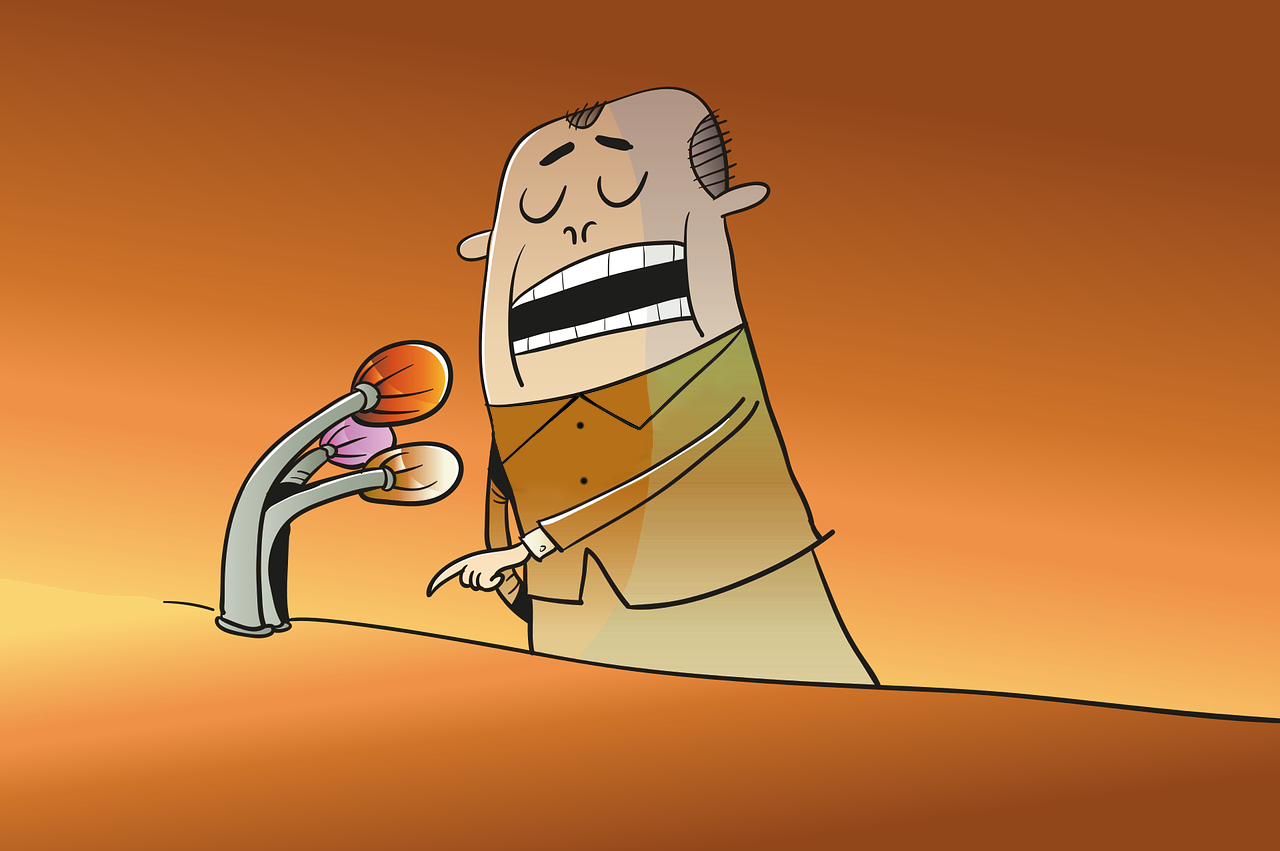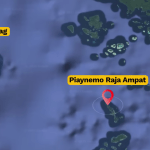Di bawah komando Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), ribuan kepala desa (kades) menjajal unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Selasa kemarin (detik.com, 2023).
Dengan suara bulat mereka meneriakan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa periodisasi. Alasannya, durasi waktu 6 tahun tidak cukup untuk membangun konsolidasi pasca pilkades dan merealisasikan program kerja (kompas.com, 17/01/2023).
Sebagai buntut dari tuntutan ini, Pasal 39 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur masa jabatan kepala desa harus direvisi. Pasal 39 terdiri dari dua ayat: “(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”
Jika desakan di atas diterima, kemungkinan revisinya adalah 6 tahun jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun, dan kemungkinan 3 kali masa jabatan dikurangi menjadi 2 tahun. Kalau dibandingkan tahun jabatan Presiden dan para kepala daerah yang lebih kompleks ruang lingkup kerjanya, 6 tahun bukan waktu yang sedikit. Lantas mengapa para kades bersikeras menuntut revisi?
Desakan tidak irasional
Alasan membangun konsolidasi dan merealisasikan program kerja tampak irasional dan tidak berbasis data-fakta. Polarisasi di kancah nasional pasca pemilu serentak 2019 terbukti dapat ditangani Presiden, padahal kadar kompleksitasnya berkali-kali lipat dari pertarungan di desa.
Semua bentuk pemilu, entah di level kota, kabupaten, provinsi, dan negara, selalu menaikan tensi, memusingkan kepala. Pertarungan sengit tidak terhindarkan. Ini justru keseruan dan konsekuensi dari sistem politik demokrasi. Jika tidak ingin bertarung dengan leluasa, sebaiknya mengambil pola monarki atau komunisme yang menutup kran kekuasaan untuk kelompok yang berbeda.
Usulan memperpanjang masa jabatan tanpa periodisasi terkesan sebagai artikulasi libido kekuasaan para kades petahana untuk mengamankan status quo dalam durasi waktu yang lama, takut tergusur lawan baru yang potensial. Tendensi semacam ini justru menyalahi prinsip demokrasi yang membuka arena tarung seluasnya untuk mengorbitkan kandidat pemimpin yang kompeten.
Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Alasan tidak cukup waktu membangun konsolidasi pasca pilkades dan mengimplementasikan program kerja justru mengindikasikan ketidakmampuan para kades untuk memimpin di desanya.
Ilmuwan S. Bowman (et.al., 2020) memerinci tiga kompetensi seorang pemimpin pada domain apapun: kepemimpinan (political and negotiation skills), teknis (strategic management), dan etis (organizational ethics). Dengan ketiga kompetensi ini, seorang pemimpin desa seharusnya mampu mengademkan suhu sosial-politik di dalam wilayah kekuasaannya dan menggolkan visi-misi kerjanya.
Karena itu, bila seorang kades keletihan dengan lekak-lekuk kontestasi politik, sudah pasti ia tidak memiliki ketiga kompetensi di atas. Kalau demikian, untuk apa memperpanjang masa jabatan kades yang cerdas dalam berdemo, tetapi inkompeten di dalam mengerjakan tugas pokoknya?
Ekses demokrasi
Sayangnya, fraksi-fraksi DPR RI menunjukkan sinyal positif untuk mengiyakan hasrat para kades (www.dpr.go.id, 17/01/2023). Usia bertemu Presiden Joko Widodo, Budiman Sudjatmiko, salah satu inisiator UU Desa, berujar Presiden pun turut mengiyakan kemauan para kades, bahkan menyiapkan skenario PP kalau UU Desa tidak dapat direvisi (www.republika.co.id, 17/01/2023).
Manuver para kades seharusnya disikapi dengan penuh kehati-hatian. Bukan kumpulan kades kalau tidak bikin heboh. Kelompok ini bahkan lancang mendeklarasikan Presiden Jokowi 3 periode (29/03/2022), sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi.
Respon bulat positif dan kilat dari para fraksi DPR dan pemerintah patut disayangkan. Ribuan tahun lalu, pemikir Aristoteles pernah mengingatkan ekses dari demokrasi (Politics, 1932). Demokrasi menjadi distorsif karena membiarkan banyak orang yang tidak berwawasan menentukan kebijakan.
Sebagai negara demokrasi, ruang publik tentu saja terbuka luas untuk aspirasi setiap kelompok. Namun peradaban demokrasi menuntut dialektika argumentatif menggunakan rasionalitas publik untuk menyensor setiap aspirasi. Tujuannya, tidak terjebak dalam isu yang partikular dan moody, bukan asal mengaut (taken for granted).
Demokrasi rentan menjadi otoritarianisme ketika kekuasaan dibiarkan lama berada di tangan satu orang. Kekuasaan itu memikat. Sekali dicicipi, akan ketagihan. Orang menjadi lupa diri karena kelamaan berkuasa. Di sinilah letak warning Lord Acton, “Power tends to corrupt; and absolute power corrupts absolutely’’ (J. Rufus Fears, 1984).
Letak persoalannya bukan pada pendeknya durasi, melainkan inkompetensi para pemimpin desa. Maka, daripada merevisi UU Desa, yang lebih krusial adalah menyaring kades yang berkualitas, dan atau melakukan upskilling and reskilling terhadap para kades.
Aspirasi para kades tentu saja tidak menyalahi aturan, tetapi tidak etis dan rasional untuk menyembunyikan kelemahan diri sendiri dengan mencari alibi. Mengakui kekurangan diri sendiri adalah satu langkah maju seorang pemimpin memperbaiki dirinya.