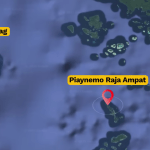Indonesia akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024. Pemilu tahun 2024 akan berbeda dengan pelaksanaan pemilu yang pernah terjadi sebelumnya. Penekanannya yakni pileg (Pemilu Legislatif), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), dan Pilpres (Pemilihan Presiden) akan diadakan pada tahun yang sama, tetapi dengan waktu (bulan) yang berbeda. Sebagai warga negara kita tentu tidak ingin politik identitas yang terjadi pada pemilu sebelumnya terulang kembali pada tahun 2024. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan daerah dan akan ternoda jika para politisi masih memanfaatkan polarisasi yang terjadi di masyarakat untuk kepentingan pemenangan.
Apa bentuk polarisasi yang saat ini mewarnai landscape perpolitikan Indonesia? Indonesia sebagai negara kesatuan terbentuk dari kelompok ideologi (religius, nasionalis, dan sosialis). Perbedaan tersebut membentuk identitas sosial yang tidak hanya menjadi berkat, tetapi juga kutuk. Dikatakan demikian karena kuatnya ikatan sosial internal kelompok dan disisi lain munculnya bias atau prasangka terhadap kelompok eksternal. Polarisasi sosial tersebut telah membentuk masyarakat Indonesia yang terbagi atas kelompok religius yang memperjuangkan negara agama, kelompok nasionalis yang tetap mempertahankan NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi tunggal, dan kelompok sosialis yang mengutamakan hak dan keadilan ekonomi.
Belajar Dari Bapak Bangsa
Pertanyaannya, identitas seperti apa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap individu untuk mengurangi polarisasi? Sudah saatnya setiap individu menghidupi identitas kebangsaan. Ada dua tokoh yang dinilai mempunyai identitas kebangsaan yakni H.O.S. Tjokroaminoto dan Soekarno. Identitas kebangsaan yang melekat dalam diri dua pribadi tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara mereka menengahi perdebatan ideologis.
Tjokroaminoto merupakan tokoh bangsa yang mendirikan Serikat Islam (1912). Di tengah perjuangannya membebaskan masyarakat pribumi dari penjajahan, ia terbentur dengan sikap para anggota Serikat Islam mempertentangkan ideologi, baik itu ideologi religius, nasionalis, dan sosialis demi sebuah visi dan misi perjuangan. Di tengah pertentangan tersebut, Tjokroaminoto berpegang teguh pada prinsip yang dianutnya yakni ketiga ideologi harus ada dalam diri masing-masing pribadi anggota Serikat Islam.
Ketika berbagai ideologi tersebut dipertahankan oleh masing-masing kelompok, maka potensi perpecahan bisa saja terjadi. Selain itu, cita-cita perjuangan pembebasan dari penjajahan tidak akan terwujud. Jiwa religius, nasionalis, dan sosialis yang ada dalam setiap individu akan membentuk jati diri kebangsaan yang kuat dan akan berguna bukan hanya menjadi tameng dalam menghadapi dominasi penjajah, tetapi juga bisa menjadi alat pemersatu untuk kepentingan bangsa. Sayangnya konsep ini tidak mampu dipahami dan dijalankan dengan baik oleh Semaun dan Kartosoewirjo.
Tokoh kedua yang dapat kita pelajari yakni Soekarno, salah satu murid Tjokroaminoto yang menganut ideologi nasionalis. Ia mampu menerjemahkan secara baik konsep sang guru. Dalam perjalanan waktu, Soekarno menyadari bahwa ideologi nasionalis tidak cukup dijadikan dasar negara. Setelah kemerdekaan Soekarno dan berbagai kelompok golongan diberi tugas untuk merumuskan dasar negara yang bisa dijadikan pegangan. Proses perdebatan yang terjadi pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan sikap Soekarno dalam menengahi perdebatan sangat relevan dengan situasi sosial saat ini.
Dalam sidang BPUPKI kelompok religius berpendapat bahwa seharusnya agama Islam menjadi dasar negara mengingat besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia. Sebaliknya kaum nasionalis tidak setuju ideologi agama tertentu menjadi dasar negara. Soekarno menyadari bahwa berbagai ideologi tersebut telah dihidupi oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Proses perdebatan yang terjadi pada sidang BPUPKI menunjukkan kekayaan pandangan masyarakat Indonesia dan penyatuan ideologi dalam Pancasila menunjukkan bahwa Soekarno ingin agar perbedaan tersebut tetap dijaga.
Menjadi Pribadi Religius, Nasionalis, dan Sosialis
Tjokroaminoto dan Soekarno telah menunjukkan tiga hal. Pertama, perdebatan bukan suatu kompetensi menang-kalah, tetapi merupakan dialektika yang berupa pertempuran gagasan demi mencari nilai yang terbaik untuk diterima semua pihak. Kedua, Bangsa Indonesia memiliki berbagai ideologi yang bisa dilihat sebagai kekayaan bangsa. Dasar negara harus memfasilitasi berbagai ideologi untuk membangun bangsa Indonesia. Ketiga, dua poin di atas tidak bisa terpenuhi, jika tidak ada proses internalisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap individu untuk menerima dan menghidupi nilai religius, nasionalis, dan sosialis.
Pada titik ini, ketiga nilai tersebut tidak lagi diartikan secara ideologis, tetapi moralitas. Mengapa demikian? Jika ketiga nilai tersebut diartikan secara ideologis, maka peluang untuk dijadikan alat politik sangat mungkin terjadi. Hal inilah yang dihidupi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Kita bisa katakan bahwa hal ini merupakan produk sejarah atau genealogi bangsa yang masih kita hidupi sampai saat ini.
Identitas kebangsaan yang mengutamakan moralitas merupakan sintesis dari proses dialektis antara nilai religius, nasionalis, dan sosial masa lalu dengan konteks saat ini. Ketiga nilai ini dibaca secara kontekstual untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Jika sebelumnya, ketiga nilai tersebut dihidupkan secara tunggal dalam diri masing-masing pribadi, maka dalam konteks saat ini semuanya harus menyatu dalam dalam diri tiap-tiap individu. Saat ini, Bangsa Indonesia sangat membutuhkan kualitas tersebut, secara khusus dalam mengurangi tensi pemilu yang sarat kepentingan dan konflik.