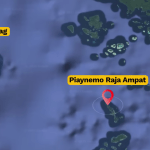Karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menjadi buah bibir di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Saking populernya, buku berjudul How Democracies Die yang terbit tahun 2018 ini pun didapuk sebagai Best Seller. Mengapa tulisan kedua ilmuwan politik ini menarik, padahal tidak menohok? Kupasannya pun seperti umumnya, sekadar deskriptif dan komparatif.
How Democracies Die lahir dari konteks kursi kepresidenan Amerika Serikat. Negara yang paling sukses dan paling lama sejarah peradaban demokrasinya, direbut oleh Donald Trump. Levitsky and Ziblatt gelisah bukan kepalang. Keduanya yakin Trump akan menggiring Amerika Serikat ke ujung tanduk.
Demokrasi Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan negara modern pertama, tersukses, dan terlama yang menganut nilai-nilai demokrasi. Di dalam bahasa Danielle Allen, kecuali Amerika, belum ada negara manapun yang berhasil membangun demokrasi multietnik dengan kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi.
Gunnar Myrdal, ahli ekonomi Swedia dan peraih Nobel menyebut kebebasan individual dan kesetaraan (egalitarianisme) sebagai American creed (1944). Kedua asas politik demokrasi ini dihidupi warga Amerika bahkan sejak saat negara digdaya itu masih dalam fase memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme Inggris. Usai meraih kemerdekaan, iklim demokrasi menguasai seluruh bilik hidup warga belahan utara benua Amerika tersebut.
Kecocokan warga Amerika dengan sistem politik demokrasi bahkan disaksikan sendiri oleh ilmuwan politik dari luar. Alexis de Tocqueville menjadi salah satu pemikir yang mengacungi jempol terhadap merembesnya nilai demokrasi ke dalam seluruh sekat hidup warga Amerika (Democracy in America, 2010). Selain pengamat politik Perancis tersebut, ahli hukum Louis Brandeis juga menyanjung Amerika sebagai “laboratorium politik”.
Membunuh Demokrasi
Prestasi di atas terancam di tangan Trump. Ketika Partai Republik yang disokong kelompok ekstrimis Amerika memenangkan Trump, Levitsky and Ziblatt mengamati gelagat Trump mengubah raut wajah Amerika. Laboratorium demokrasi tengah direhab menjadi “laboratorium otoritarianisme”. Namun, bagaimana Trump dapat menjadi arsitek despotik yang mencabut fondasi demokrasi negeri Paman Sam?
Levitsky dan Ziblatt mengatakan ancaman terhadap demokrasi bukan lagi komunisme, kudeta militer, atau fasisme. Jurus baru yang efektif, halus, bertahap, dan bahkan legal untuk membunuh demokrasi justru berasal dari dalam sistem demokrasi sendiri.
Pemimpin negara dipilih secara demokratis. Namun usai berkuasa, ia memanipulasi institusi demokrasi seperti pemilu, konstitusi, pers, dan pengadilan untuk mengamankan kekuasaannya. Aturan pemilu ditulis kembali. Konstitusi digaris ulang. Hak pilih warga pun dapat dicabut. Hasil pemilu dengan mudah ditolak dengan rasionalisasi kecurangan.
Bagi kedua penulis ini, Trump adalah demogog. Ia tidak paham nilai demokrasi masyarakat Amerika yang telah berurat akar ratusan tahun. Karena itu, kemenangan Trump merupakan katastrofe nasional yang menandai abad kegelapan demokrasi. Ironinya, tidak banyak warga Amerika yang siuman dari sihir Trump. Tidak sedikit yang masih mengkultuskan Trump sebagai spiderman Amerika yang mampu make America great again.
Erosi demokrasi ini implisit, sulit untuk ditembus mata biasa, sehingga efektif. Untuk itu, Levitsky and Ziblatt menyuling empat indikator untuk mendeteksi aura otoritarian seorang pemimpin negara. Diukur melalui sikap menolak atau memiliki komitmen yang lemah terhadap aturan main demokrasi; menyangkal legitimasi lawan politik; menoleransi kekerasan; dan membatasi kebebasan sipil lawan politik, termasuk media.
Persis keempat fitur di atas dilakonkan Trump. Ia menyisipkan orangnya, Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh di Mahkamah Agung untuk mendapat kekebalan hukum. Ia menolak dikalahkan Joe Biden pada pemilu Amerika 2020 dan menghasut massanya untuk menyerang Kapitol pada 6 Januari 2021. Di Partai Republik, Trump memegang kendali. Sebelum Trump, Hugo Chavez di Venezuela adalah contoh representatif presiden yang dipilih secara demokratis, tetapi berujung otokratis.
Menyelamatkan Demokrasi
Kalau demikian, bagaimana menyelamatkan demokrasi? Menurut Levitsky dan Ziblatt, Konstitusi saja tidak cukup. Konstitusi harus ditopang oleh partai politik, kesatuan warga yang terorganisir, dan norma demokratis. Poin terakhir menjadi paling desisif di dalam situasi kemelut. Kedua ilmuwan politik tersebut yakin, versi terbaik demokrasi Amerika dapat berjalan jika konstitusinya diperkuat oleh norma-norma demokratis yang tidak tertulis. Kedua norma itu ialah toleransi timbal-balik dan kesabaran institusional.
Kebebasan dan kesetaraan hanyalah nilai yang self-justifying, bukan self-executing. Karena itu, dibutuhkan norma lain, yakni toleransi timbal-balik dan kesabaran institusional. Kedua norma tersebut merupakan prinsip prosedural yang menunjukkan bagaimana politisi dapat berperilaku, mengatasi ikatan hukum, untuk memfungsikan lembaga-lembaga negara.
Toleransi timbal-balik mengimplikasikan partai-partai yang berkompetisi saling menerima sebagai rival yang sah. Sementara itu, kesabaran institusional mengharuskan para politisi menahan diri di dalam menggunakan hak prerogatif kelembagaannya. Ketika rival politik dipandang sebagai musuh, kompetisi menjadi medan perang berdarah (Carl Smith, 1996).
Tanpa keutamaan mawas diri, politisi dan pejabat publik dapat menginstrumentalisasi institusi-institusi sebagai senjata untuk memberangus lawan. Akibatnya, sistem demokrasi mengalami krisis mendalam. Institusi memiliki dua makna mendasar (Ricoeur, 1999; Ricoeur, 2000).
Pertama, secara ontologis-eksistensial, institusi mengacu pada situasi primordial pra-etis yang menentukan hidup setiap orang. Setiap orang lahir sudah berada dalam an after-the-fact situation. Ia tidak pernah memulai dari nol. Karena itu, tindakan setiap individu, bukan hanya politisi, memiliki batasan tidak tertulis yang sudah mengikat sejak ia terlempar ke dalam dunia.
Kedua, secara pragmatis-politis, institusi adalah nilai dan norma sosial yang diformalkan. Kategori kedua ini tidak sekadar institusi sebagai aturan formal, melainkan pemahaman bersama (shared understandings) tentang perilaku normatif tertentu.
Politisi itu bukan pribadi, melainkan lembaga. Kekuasaan melekat di dalam lembaga sehingga cenderung koruptif. Karena itu, sistem demokrasi membatasi kekuasaan setiap politisi dan pejabat publik dengan mendorong penubuhan (embodiment) toleransi mutualis dan mawas diri dalam menyampaikan aspirasi. Di sini letak pentingnya setiap pejabat publik dan politisi menghidupi etika publik.
Etika Publik
Etika publik merefleksikan prinsip-prinsip moral individu di dalam konstelasi ruang publik, terutama pejabat publik dan politisi. Etika publik diperlukan untuk mengontrol kekuasaan yang melekat pada setiap pejabat publik dan politisi, tetapi kekuasaan tersebut luput dari jeratan hukum (Haryatmoko, 2011).
Mengapa politisi juga harus tunduk pada etika publik? Tidak ada politisi sebagai individu semata. Di belakang politisi selalu ada institusi, entah partai politik, lembaga negara, entah nilai-nilai sosial masyarakat.
Di dalam praksis hidup harian, pejabat publik dan politisi harus memiliki “arete” (Bunnin and Yu, 2004) atau keutamaan. Keutamaan adalah kebijaksanaan praktis atau kemampuan seseorang mendaratkan prinsip-prinsip moral di dalam tindakan nyata.
Di sini kita paham, mengapa konstitusi perlu ditopang oleh norma? Atau mengapa politisi dan pejabat publik harus mawas diri? Hukum tidak melarang seorang presiden atau pemimpin lembaga tinggi negara untuk berpolitik, tetapi etika politik membatasi.
Hukum tidak dapat menarik garis demarkasi tegas di dalam realisme politik yang samar-samar, karena bukan ranahnya. Realisme politik acapkali blurred ketika berhadapan dengan situasi dilema yang menuntut diskresi moral. Ini adalah arena bermain etika publik, yang mampu membedakan dikotomi “yang seharusnya” (the ought, das sollen) dan “yang ada” (the is, das sein).
Yang ada mengartikulasikan fakta, apa yang ada, sedangkan yang seharusnya mengungkapkan relasi manusia dan kecondongan subjektif atau ekspresi nilai, sesuatu yang diperjuangkan. Bagi David Hume dan Immanuel Kant, yang seharusnya tidak dapat disimpulkan secara logis dari yang ada karena premisnya terletak pada tendensi subjektif tentang apa yang dihasrati dan atau dalam konsensus masyarakat tentang apa yang diijinkan (Simms, 2003).
Merger secara paksa antara yang seharusnya dan yang ada justru akan menghasilkan totalitarianisme (Gaus, 2016). Panggung politik selalu berada dalam tegangan antara fakta praksis politik di lapangan dan prinsip atau ideal-ideal politik. Menyerobot batas di antara yang ada dan yang seharusnya akan menimbulkan keriuhan.
Namun, yang ada seyogyanya bercermin pada yang seharusnya untuk menghasilkan keteraturan dan rasionalitas (Kant, 1952). Supaya tidak menjadi totaliter, pendaratan idealitas demokrasi harus didasarkan pada keutamaan publik. Namun tidak semua orang mampu, hanya pejabat publik atau politisi. Karena itu, menjadi pejabat publik atau politisi adalah prestasi sekaligus tanggung jawab etis.
Kita harus ingat, kemampuan untuk membaca dan melihat dengan jernih kejelasan di dalam kesamaran dunia politik dan bertindak di atas kepastian kebenaran tersebut embedded secara institusional di dalam nomenklatur pejabat publik dan politisi. Seorang pejabat publik secara etis tidak boleh berpolitik karena kekuasaan yang melekat pada dirinya dapat disalahgunakan atau mencelakai lawan politik.
Pejabat publik salah secara etis jika ia mengeksploitasi ruang kosong dalam realisme politik yang tidak dipayungi hukum untuk mengamankan kepentingannya. Tujuan dan motivasi baik saja tidak cukup untuk membenarkan sebuah tindakan. Bentuk eksternal tindakan juga harus dipertimbangkan. Jika para politisi dan pejabat publik kita tidak mengindahkan moralitas sosial, Indonesia 2024 mungkin akan berwajah Amerika Serikat 2020.