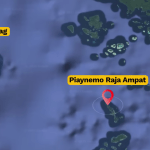Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media sosial terbesar di dunia. Laporan We Are Social dan Hootsuite, seperti yang dikutip DataIndonesia.id menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 60,4% dari total populasi penduduk tanah air pada Januari 2023. Pada tahun 2022, lembaga yang sama juga merilis bahwa Indonesia berada di urutan 10 penggunaan media sosial di dunia. Dalam sehari masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 16 menit dalam menggunakan media sosial. Jumlah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat global dalam menggunakan media sosial yakni 2 jam 29 menit per hari.
Media sosial saat ini tidak hanya dijadikan alat untuk mempererat pertemanan, tetapi juga untuk memperoleh atau menyebar informasi. Salah satu fenomena menarik dalam dunia maya yakni viral. Kata viral merujuk pada hal yang sangat populer di media sosial. Contoh yang menarik mengenai hal ini yakni ketika Bima Yudho Saputro (kreator media sosial) menyebut pemerintah Provinsi Lampung sebagai dajal (setan) di media sosial karena dinilai tidak memperhatikan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Kritik tersebut populer di media sosial dan mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Beliau bersama menteri terkait meninjau langsung kondisi jalan yang rusak.
Paradigma Baru Dalam Ruang Publik
Fenomena viral dalam ruang publik telah mengalami pergeseran paradigma. Daya penggeraknya yakni perkembangan teknologi yang ditandai menjamurnya penggunaan media sosial. Sebelum media sosial menjadi bagian dari ruang publik, pembicaraan dalam ruang publik bersifat top-down. Artinya, hanya pemerintah, akademisi, atau lembaga sosial berdiskusi mengenai isu tertentu dan peran masyarakat hanya sebagai penonton pasif. Ketika media sosial hadir, pembicaraan bersifat bottom-up. Masyarakat aktif berbicara mengenai isu yang mereka rasakan dan ruang baru ini telah terbukti mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan dua nilai penting. Pertama, kita patut mengapresiasi bahwa kehadiran media sosial membawa dampak positif yakni mampu mengembalikan peran masyarakat dalam ruang publik. Ruang publik selama ini diisi dengan percakapan yang sifatnya feodal. Artinya masalah yang dibicarakan merupakan masalah yang dipikirkan oleh pemerintah dan bukan masyarakat. Kedua, Kehadiran media sosial membuat masyarakat berani untuk melakukan kritik atau meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sikap ini ingin mengembalikan sikap apatis atau ketidakpedualian masyarakat atas kinerja pemerintah yang selama ini dinilai berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Media Sosial Sebagai Instrumen Pengawasan
Pergeseran paradigma peran masyarakat dalam ruang publik dari masyarakat pasif ke masyarakat aktif yang ditopang oleh media sosial harus dikondisikan dalam kanal yang tepat. Kanal tersebut yakni pengawasan kinerja pemerintah. Apa alasannya? Kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah masih saja terjadi saat ini. Data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejak tahun 2004-2022 terdapat 22 gubernur dan 154 walikota/bupati dan juga wakil yang berurusan dengan KPK. Jumlah tersebut belum termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebanyak 310 anggota dewan juga terjerat korupsi pada periode yang sama. Sebagian besar bentuk korupsi yang dilakukan oleh mereka yakni penyelewengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
Korban utama korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tentu saja masyarakat. Tingginya angka korupsi kepala daerah dan lemahnya kemampuan pengawasan menjadi imperatif bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan media sosial. Apa bentuk konkret pengawasan yang dilakukan masyarakat? Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni membaca dan menganalisis APBD yang berisi program dan anggaran berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan wilayah. Program dan anggaran yang butuh klarifikasi dan harus diketahui oleh publik bisa menjadi konten untuk diperbincangkan di media sosial.
Pertanyaannya, apakah tindakan pengawasan tersebut melanggar norma sosial dalam ruang publik? Saya berpikir tentu saja tidak. Dalam kaitannya dengan hal ini, bentuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kepala daerah atau anggota dewan yang dipilih melalui mekanisme pemilu diberi wewenang untuk menata pemerintahan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengetahui kinerja pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk mendiskusikan secara luas program dan anggaran pemerintah. Media sosial dapat menjadi ruang yang tepat bagi masyarakat agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik.
Media sosial mungkin dinilai bukan ruang yang tepat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Penilaian seperti ini tentu saja mempunyai dasar yang kuat karena ruang media sosial tidak mengkondisikan diskusi yang mengedepankan sopan-santun. Media sosial sebagai anak kandung pengetahuan mempunyai satu kelemahan yakni tidak mempunyai kapasitas sendiri untuk menentukan norma sosial yang mengatur dirinya. Meskipun demikian, kelemahan ini tidak bisa menjadi penghalang agar pengawasan dari masyarakat itu terus berjalan. Ruang media sosial merupakan ruang dialektika yang dipenuhi dengan pertukaran ide dari berbagai perspektif dan mempunyai satu tujuan tunggal yakni kebaikan bersama (bonnum commune).