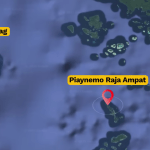Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perhelatan Pemilu berikutnya pada 14 Februari (kominfo.go.id, 2022). Semua partai politik (parpol) bersorak menyambut kabar tersebut. Kalangan selebritas ramai berbondong-bondong ikutan ‘nyaleg’ (seleb.tempo.co, 2023). Meskipun terasa gegap gempitanya, pesta demokrasi kita sejak fajar reformasi menyingsing ibarat pedang bermata dua. Selayang pandang kelihatan raut wajahnya bersukaria, tetapi auranya pembunuh. Alhasil, kericuhan yang memakan korban sering tidak terhindarkan pada fase pemungutan suara dan hitungan hasil.
Di pekan ketiga Mei, terdapat beberapa isu mendapat sorotan pemberitaan. Selain kompetisi Sea Games di Gamboja, banyaknya artis mendaftarakan diri sebagai calon legislarif 2024 di beberapa parpol menjadi buah bibir. Aksi saweran kader Golkar di halaman kantor KPU di Sumatera Selatan semakin menunjukkan permainan uang terang-terangan pada pemilu mendatang. Jebakan investasi China melalui megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga turut menjadi pembahasan serius para ahli. Terakhir, Gubernur Lampung seakan tak henti menimbulkan kontroversi setelah melarang wartawan meliput setiap aktivitasnya. Fenomena politik uang menjadi pembahasan artikel ini.
Kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot yang diterbitkan dalam buku ‘Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia’ menunjukkan derasnya arus money politics di Indonesia. Tidak hanya permainan uang tunai, tetapi juga aneka transaksi lain yang disebut dengan klientelisme. Berbeda dengan negara demokrasi lain seperti Argentina dan India yang juga klientelistik, pola Indonesia lebih liar, ganas, dan berurat-akar. Aspinall dan Berenschot menyebutnya freewheeling clientelism di dalam pusaran patronage democracy atau plutokrasi karena hanya bisa mengorbitkan orang-orang berkelimpahan kapital. Istilah khas Jawanya ialah demokrasi wani piro.
Akibat demokrasi wani piro, korupsi sistemik sulit diputus. Bagaimana mungkin politisi tidak melakukan KKN jika ia mengeluarkan biaya begitu banyak selama proses pencalonannya? Korupsi di masa Orde Baru bahkan lebih terukur dibandingkan era reformasi. Jika korupsi era Soeharto terjadi ‘di bawah meja’, di era kita justru terang-terangan dilakukan ‘di atas meja’ (Sholikin, Mei 2019).
Aspinall dan Berenschot bahkan kebingungan mencari resep ampuh untuk meminimalisir transaksi politik di Indonesia. Keduanya mengakhiri buku tersebut dengan memberikan usulan normatif, yakni parpol harus memainkan peran lebih besar untuk mengontrol kadernya. Namun, dua peneliti senior ini pun mengakui penguatan struktur parpol juga tidak steril permainan uang sebagaimana terjadi pada demokrasi Thailand.
Meskipun membutuhkan waktu yang lama, mengikis akar praksis klientelisme dalam demokrasi Indonesia bukan hal mustahil. Misteri memang tidak punya jawaban, tetapi masalah selalu miliki jawaban. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat, mahalnya ongkos politik dapat diberantas dengan pendidikan politik dan penguatan kontrol hukum (Indrayana, 2017).
Solusi Denny tersebut direkomendasikan juga oleh Nur Syamsudin, Iqra Arbiyani, dan Sulfikar Sallu. Namun, ketiga peneliti tersebut menambahkan beberapa hal, meliputi moratorium money politics, sosialisasi, pendidikan politik, reformasi dalam legislasi, gerakan bersama, khutbah dan konseling religius (Syamsudin, et.al.,2018). Meskipun begitu, usulan pembenahan hukum serupa pernah diusulkan Senator Amerika Bernard Sanders untuk merehabilitasi demokrasi liberal Amerika yang terjebak di dalam korupsi plutokratis, tetapi terbukti tidak efektif (Hager, 2023).
Ilmuwan politik Uni Eropa, Lawrence Pratchett dan Vivien Lowndes, menawarkan tiga cara berbeda. Pertama, standar etika yang tinggi, selain kontrol hukum, terhadap semua pelayan publik. Kedua, mengembangkan instrumen untuk menangani korupsi di tingkat lokal hingga nasional dan internasional. Ketiga, mendorong dan merawat kebebasan pers dan media sosial sebagai kontrol publik (Pratchett and Lowndes, 2004).
Di tempat terpisah, lembaga People For the American Way mengusulkan reformasi komprehensif sistemik berupa amandemen konstitusi, menyediakan pendonoran public funding, transparan terhadap political spending, dan aturan pendanaan kampanye yang kuat (pfaw.org). Usulan public funding dipandang paling relevan oleh ilmuwan politik Julia Cage (Patrick Camiller, 2020). Namun public funding tanpa regulasi akan ludes.
Lembaga konsultan politik International IDEA mengakui demokrasi itu mahal karena membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memungkinkan kampanye, representasi, dan partisipasi politik. Namun, jika tidak diregulasi dengan efektif, akan merusak integritas institusi dan proses politik, serta membahayakan kualitas demokrasi (idea.or.id). Maka, public funding harus dilegalisasi sebagaimana diusulkan Magnus Öhman Director, pejabat regional Eropa dan penasehat senior keuangan politik. Ia mendorong akses terhadap funding yang legal (ifes.org, 2013). Dengan kata lain, public funding harus difasilitasi negara. Itu artinya, ongkos politik pemilu ditanggung seluruhnya oleh negara. Konsekuensi logisnya, pertama, kandidat politik hanya maju dengan gagasan. Kedua, jumlah partai harus dibatasi, bukan jumlah kandidat, untuk mengurangi biaya operasionalisasi.