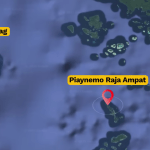Pilkada telah berlangsung pada 27 November 2024 diikuti sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Menjadi pesta demokrasi yang penting bagi rakyat untuk terlibat menentukan pemimpin daerah dalam periode baru. Ada yang bangga berhasil memenangkan calonnya sebagai kepala daerah. Ada yang harus mengakui kekalahan sebagai bagian dari proses berdemokrasi.
Kini, rakyat tengah menanti sang pemenang kontestasi dilantik oleh KPU untuk menahkodai masing-masing daerah di Indonesia sepanjang lima tahun mendatang. Selain menunggu momentum pelantikan, rakyat di beberapa daerah juga harap-harap cemas dengan hasil sidang sengketa pilkada yang berlangsung di MK.
Lantas, sudahkah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah berlangsung sebagaimana makna berdemokrasi? Jika dilihat dari praktik demokrasi yang terjadi dalam Pemilihan Umum 2024, sejatinya praktik berdemokrasi masih tertinggal jauh dari substansinya. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya praktik politik transaksional.
Sebagaimana dalam riset yang dilakukan oleh Burhanuddin, ia mengatakan bahwa tren pewajaran politik uang mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data yang ia himpun besaran masyarakat yang mewajarkan politik uang di tahun 2024 berada di kisaran 54,5 persen atau mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen sejak tahun 2006 (Nefi P, 2024).
Praktik politik transaksional juga sempat disampaikan Prabowo dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar. Alasan Prabowo melemparkan gagasan untuk menghapus sistem pilkada langsung karena adanya politik transaksional, bersifat elitis, dan merampas hak pilih orang banyak.
Dalam sejumlah kasus, kandidat kepala daerah mengeluarkan banyak uang untuk dua agenda besar, yakni kebutuhan belanja suara dan biaya perolehan tiket pemilihan. Praktik politik uang dengan calon pemilih terjadi di tempat terang, sedangkan mahar kandidat partai pendukungnya diberikan dalam ruang gelap. Fenomena tersebut menurut Prabowo menyebabkan biaya politik tinggi (Tempo, 2024).
Keinginan Prabowo untuk menghilangkan pemilihan langsung dianggap lebih buruk karena berusaha untuk menyingkirkan rakyat sebagai public interest. Kepentingan publik dapat dimaknai dalam situasi rakyat yang berkuasa dan rakyat yang memerintah. Di mana pemerintahan oleh rakyat dengan perantaraan pemimpin daerah dan wakil rakyat yang dipilih secara langsung. Namun, sudahkah rakyat sebagai public interest berdemokrasi secara baik? Atau malah menjadi budak dari sistem berdemokrasi?
Sebagaimana dalam sistem demokrasi Yunani Kuno, rakyat ditempatkan berdasarkan status. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, pengertian ‘rakyat’ dalam teori kenegaraan Yunani Kuno, terbagi menjadi tiga kelas pokok. Kelas pokok pertama, para budak sebagai kelas masyarakat terendah; kelas pokok kedua yakni penduduk asing atau meties, kedua kelompok ini merupakan budak politik karena tidak mempunyai hak politik; kelas pokok ketiga terdiri atas warga anggota ‘negara kota’ dan berhak ambil bagian dalam kehidupan politik atau jabatan dalam pemerintahan (Ali, dkk. 2016).
Potret pragmatisme politik elektoral 2024 menempatkan rakyat Indonesia pada kategori kelas pokok kedua, yakni budak politik. Dikatakan sebagai budak politik karena kebebasan rakyat seutuhnya ditukar dengan iming-iming berupa nilai nominal maupun finansial. Akibatnya pemilihan pemimpin bukan karena kehendak suara hati, melainkan karena keinginan untuk mendapatkan uang, bantuan, atau manfaat material lainnya. Alhasil, proses demokrasi yang menjadi cita-cita bersama menjadi kehilangan esensinya.
Di Indonesia, pemimpin yang dipilih atau dihasilkan umumnya dilihat dari banyaknya uang yang diberikan, bukan dari kualitas yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Akibatnya praktik demokrasi belum menjadikan suara rakyat sebagai suara malaikat. Rakyat masih dikategorisasikan sebagai orang-orang yang menjadi budak dari uang dan dianggap tidak mempunyai hak apapun. Bahkan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjualbelikan.
Rakyat masih terikat pada kompensasi yang menjadikan dirinya sebagai budak dari proses demokrasi. Padahal, sejatinya inti dari proses demokrasi terletak pada jaminan akan hak-hak yang berdasarkan pada pengertian kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Setiap orang menjadi tuan atas dirinya sendiri yang mampu bertanggungjawab terhadap suara hatinya.
Berhadapan dengan persoalan ini, sependapat dengan Ros Harrison, ada dua kesadaran yang mesti dibangun oleh rakyat. Pertama, rakyat harus menyadari dirinya sebagai tuan atas dirinya sendiri. Dengan demikian, otonomi diri merupakan suatu kesadaran yang harus ditanamkan dalam pikiran masyarakat. Nilai otonomi adalah nilai yang baik, karena membiarkan manusia mengatur dirinya sendiri. Sebab otonomi adalah dasar dari kehidupan berdemokrasi. Tanpa otonomi tidak akan ada demokrasi (Wattimena, 2024).
Kedua, rakyat juga mesti menyadari diri sebagai makhluk yang setara. Sebagaimana dinyatakan oleh Harrison bahwa demokrasi hanya bisa tercipta apabila ada kesetaraan di masyarakat. Sebab rakyat adalah subjek dari hukum yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Bukan menjadi budak dari politik. Dengan demikian warga negara menjadi public interest yang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik secara demokratis.