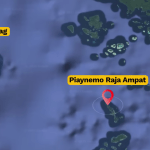Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan telah menjadi sorotan tajam di ruang publik. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025 yang bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Proyek bertujuan memperbarui buku sejarah nasional dengan menghapus bias kolonial, menegaskan perspektif yang Indonesia-sentris, menjawab tantangan global, memperkuat identitas bangsa, dan membuat sejarah lebih relevan untuk generasi muda hari ini. Namun di balik narasi tersebut muncul kekhawatiran, apakah penulisan ulang ini akan benar-benar membuka ruang bagi kebenaran sejarah atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan?
Penulisan ulang sejarah memang diperlukan terutama untuk memasukkan temuan-temuan baru, seperti lukisan gua berusia 50.000 tahun di Sulawesi Selatan, atau koreksi atas narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Selain itu, upaya ini menjadi semakin relevan karena proses transisi politik di Indonesia hingga kini belum sepenuhnya menuntaskan berbagai kejahatan masa lalu, termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia.
Proyek penulisan ulang sejarah ini tidak luput dari sorotan kritis. Salah satu kritik datang dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang mempertanyakan motif, metode, dan dampaknya terhadap kebebasan berpikir serta integritas sejarah itu sendiri. Prosesnya yang dinilai tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik.
Target sepuluh jilid dalam waktu yang sangat singkat memunculkan kekhawatiran mengenai kedalaman riset, kesinambungan antarjilid, serta keterhubungan antarpenulis. Padahal, penulisan sejarah seharusnya menjadi proses terbuka yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan para penyintas sejarah, bukan sekadar ditentukan oleh segelintir aktor yang terpilih secara tertutup.
Lebih jauh, terdapat kekhawatiran bahwa proyek ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Pemberian label sejarah resmi dikhawatirkan memberi risiko besar terhadap keberagaman narasi. Pendekatan tunggal dalam penulisan sejarah berpotensi mengesampingkan versi-versi lain yang berbeda, mengkriminalisasi narasi alternatif, serta membatasi ruang koreksi dan evaluasi di masa mendatang.
Penekanan berlebihan pada narasi kejayaan masa lalu juga mengandung risiko tersendiri. Glorifikasi sejarah dapat memicu munculnya nasionalisme yang agresif sehingga cenderung tidak menerima perbedaan dan menekan suara-suara kritis. Hal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik-praktik diskriminatif. Padahal sejarah bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga tentang kekalahan, kekerasan, dan luka kolektif yang perlu dikenali agar tidak terulang.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengkhawatirkan substansi dalam penulisan ulang sejarah ini berpotensi mengaburkan sejumlah peristiwa penting seperti pembunuhan mahasiswa pada 1998, penculikan aktivis, gerakan perempuan, hingga Papua. Bahkan, narasi tentang Kongres Perempuan 1928 yang bersejarah pun tampak kurang mendapat perhatian. Hal ini mengindikasikan bahwa versi sejarah yang akan disusun berisiko mengabaikan banyak suara, khususnya dari kelompok marjinal dan para korban kekerasan negara.
Pelabelan ‘resmi’ terhadap sejarah menciptakan hierarki kebenaran yang berpotensi mengancam kebebasan berpikir. Kondisi ini dapat berujung pada pembungkaman kritik serta membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan melalui narasi sejarah. Sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan dijadikan alat untuk mengendalikan ideologi.
Apabila pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menghadirkan sejarah yang adil dan demokratis, maka transparansi serta partisipasi publik menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Draf naskah sejarah perlu dibuka kepada publik sebelum ditetapkan sebagai acuan resmi agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyanggah, atau menambahkan narasi-narasi yang selama ini terpinggirkan. Proses ini semestinya mencakup diskusi publik, pelibatan akademisi, serta pendengaran terhadap kesaksian para korban.
Penulisan ulang sejarah seharusnya tidak semata-mata menjadi bagian dari peringatan hari kemerdekaan, melainkan momentum kolektif untuk belajar dari masa lalu. Keberanian untuk mengakui kekeliruan, mengangkat sisi kelam sejarah, serta menghindari glorifikasi yang semu merupakan langkah krusial menuju rekonsiliasi nasional. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang membanggakan masa lalunya, tetapi juga yang mampu menghadapi luka-lukanya dengan jujur dan membangun masa depan dengan kesadaran serta empati.
Penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan sebuah proyek besar yang menyimpan potensi ganda. Proyek ini dapat menjadi ruang bagi pencarian kebenaran atau justru berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Di sinilah letak tantangan utamanya. Apakah negara akan membuka sejarah sebagai ruang dialog demokratis atau justru membatasinya dalam kerangka tunggal versi penguasa. Arah masa depan sejarah Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pertanyaan ini dijawab pada hari ini.