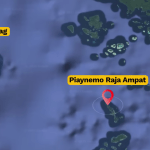UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki banyak pro-kontra semenjak masih berbentuk naskah akademik dan RUU. RUU Cipta Kerja mengandung cacat pada metodologi, paradigma, dan substansi pengaturan di bidang kebijakan. Regulasi ini pun dinilai mengabaikan prinsip sustainable development. Kemungkinan over-regulated dan over-lapping tak terhindarkan karena regulasi pembangunan dan investasi pada RUU Cipta Kerja mensyaratkan sekitar 500 aturan turunan.
Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Dengan kata lain, UU ini secara sah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang belum dilakukan perbaikan. Meskipun begitu, UU Cipta Kerja baru dinyatakan tidak lagi berlaku apabila dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan, pemerintah tidak melakukan perbaikan. Tidak sebatas itu, MK juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas seperti menerbitkan peraturan pelaksana baru sesuai UU Cipta Kerja.
Putusan MK di atas dilandasi beberapa pertimbangan. Pertama, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang pada UUD 1945 sehingga dinyatakan cacat formil. Kedua, MK hendak menghindari ketidakpastian hukum dengan melakukan perbaikan pada UU Cipta Kerja sehingga UU Cipta Kerja dapat memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketiga, UU Cipta Kerja tidak perlu nomenklatur baru karena merupakan perubahan sejumlah undang-undang, bukan sebagai undang-undang yang memiliki norma baru.
Namun, asa pemerintah memperjuangkan UU Cipta Kerja tak kunjung habis. Pada 30 Desember 2022 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Sontak tindakan Joko Widodo memanen berlapis-lapis kritik.
Beranjak dari riak di atas, PSPD UGM bekerja sama dengan Suryakanta Institute menggelar bincang akademis untuk menelaah hadirnya Perppu Cipta Kerja. Pembicara yang dihadirkan bukan ecek-ecek: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Akademisi / Ahli Hukum Tata Negara UGM), Dr. Rangga Almahendra (Akademisi / Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), dan Ardy Syihab (Perwakilan Serikat Merdeka, SEMESTA). Bincang akademis ini bertajuk “Tarik-Ulur Regulasi Cipta Kerja dalam Proyeksi Investasi Nasional.”
Di dalam perbincangan tersebut Dr. Zainal mengungkapkan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan gejala autocratic legalism. Dalam tulisannya “Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law”, Dr. Zainal mengkategorikan Omnibus Law ke dalam autocratic legalism. Ada tiga indikator autocratic legalism: (i) partai politik yang mendukung pemerintahan sangat kuat sehingga melemahkan lembaga legislatif, (ii) penyalahgunaan hukum dan konstitusi, dan (iii) intervensi kekuasaan yudikatif yang independen.
Seturut alur itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah juga pelanggaran konstitusi. Secara hierarkis kedudukan perppu sejajar dengan undang-undang. Hal ini menandakan terdapat persamaan tingkat antara undang-undang dan perppu karena materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Perppu memiliki bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang pembentukannya hanya diberikan kepada Presiden.
Kedudukan perppu yang bersifat khusus dapat menggantikan undang-undang dalam ikhwal khusus sesuai pada ketentuan UUD Pasal 22 ayat (1), “Dalam ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menunjukkan beberapa parameter “kegentingan yang memaksa” untuk menerbitkan sebuah perppu. Pertama, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Adapun tujuh kondisi yang memenuhi indikator kegentingan menurut Joko Widodo sebagaimana terlampir pada bagian pertimbangan Perppu Cipta Kerja: (i) pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (ii) penyerapan tenaga kerja dan adanya krisis ekonomi yang dapat mengganggu perekonomian nasional, (iii) perlunya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan cipta kerja, (iv) kebutuhan hukum untuk pencepatan cipta kerja, (v) perlunya terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan, (vi) pelaksanaan putusan MK yang membatalkan UU Cipta Kerja sebelumnya, dan (vii) respons terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan inflasi yang berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
Menanggapi parameter di atas, Dr. Zainal menyatakan terdapat relasi antara demokrasi dengan keadaan darurat. Ironisnya, Pemerintah menggunakan keadaan darurat untuk melancarkan ketidakdemokratisasiannya. UU Cipta Kerja hanya dibuat selama 11 bulan, tetapi diberi jangka revisi selama dua tahun. Alih-alih membuat Perppu Cipta Kerja, Pemerintah seharusnya melakukan revisi UU.
Disahkanya Perppu Cipta kerja berdampak buruk bagi hubungan antar lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan MK. Presiden dinilai tidak menghormati putusan MK sekaligus tidak menghormati DPR selaku pembentuk undang-undang. Pengesahan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU 13/2022 yang tidak memperbolehkan perppu dibuat dengan metode omnibus. Apabila dilakukan judicial review terhadap Perppu Cipta Kerja, MK harus berhati-hati dan mendengarkan kritik dari publik, mengingat peran MK sebagai the guardians of constitutions.