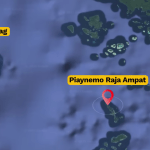Pesta selalu menggembirakan karena merayakan kesuksesan atau peristiwa lainnya yang mengandung sukacita. Namun, kenyataan tidak jarang menunjukkan pesta berakhir ricuh. Begitupun pesta politik. Menjelang pagelaran Pemilu 2024, tanda-tanda memilukan sepertinya tidak dapat dihindari. Bukan karena kekacauan, melainkan karena miskinnya transaksi politik 24 parpol (kpu.go.id, 2022) yang akan memeriahkan pesta akbar demokrasi tersebut.
Di pekan akhir April 2023, isu-isu politik menguasai kanal-kanal pemberitaan luar negeri, dalam negeri, hingga kasak-kusuk lokal. Pencapresan Ganjar Pranowo oleh sebagian besar media menjadi magnet pemberitaan. Drama Mario jilid 2 yang dilakonkan Aditya Hasibuan, anak seorang perwira tinggi Polisi Polda Sumatera Utara, terhadap seorang mahasiswa menyebabkan jabatan ayahnya dicopot. Seorang anggota Kopasgat yang menendang motor seorang ibu dan anaknya dihukum atasan dan dipaksa untuk meminta maaf. Pengejaran KKB yang menyandera pilot New Zealand masih hangat dibahas media Australia. Artikel ini akan menyoroti riuh-riah parpol kepincut aura Ganjar Pranowo.
Semakin menguat dan mengerucutnya tiga nama (Ganjar, Prabowo, Anies) yang berpeluang menjadi capres pada Pemilu 2024 mengindikasikan semakin benarnya dugaan banyak orang, terutama opini pakar hukum Denny Indrayana yang menyebutkan, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies (integritylawfirms.com, 2023). Kemungkinan besar kontestasi pilpres mendatang hanya akan dilakoni oleh dua pasangan calon, atau paling banyak tiga.
Jika skenario di atas berjalan, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukan parpol dan politisi yang merugi, melainkan masyarakat Indonesia. Rakyat kehilangan ruang untuk memilah dan memilih lebih banyak opsi calon presiden. Padahal Indonesia saat ini tidak kekurangan pasokan tokoh nasional yang berkapabilitas. Sebut saja Erick Thohir, Mahfud MD, Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama, dan beberapa tokoh lain.
Ketidakmampuan dan ketiadaan political will para petinggi parpol mencalonkan tokoh lain selain Ganjar, Prabowo, dan Anies, menunjukkan masalah serius. Masalah pertama, esensi demokrasi multipartai kita tidak lebih dari platform, bukan substansi demokrasi yang mencerminkan beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Masalah yang kedua, masyarakat kehilangan peluang untuk memilih tokoh terbaik dari lebih banyak opsi.
Kebanyakan tokoh berkualitas saat ini justru berasal dari lingkaran non-partai. Ini mengimplikasikan parpol tidak menarik dan tidak berkemampuan untuk menciptakan kader sendiri. Parpol minus kaderisasi adalah simptom sosial serius yang harus disembuhkan. Demokrasi kita sehat jika parpol bebas penyakit.
Patokan dasar rerata parpol mengusung ketiga tokoh di atas adalah elektabilitas yang tinggi berdasarkan survei. Padahal, kredibilitas survei memiliki beberapa kelemahan. Survei selalu berupa sampling yang terbatas, bahkan tidak representatif. Survei juga tidak pernah bebas ‘titipan amplop’. Selain itu, tidak ada satu survei pun yang mampu menyajikan ‘meta-analysis’ yang komprehensif. Tujuan survei utamanya menggiring opini publik, bukan merepresentasi realisme politik (Haryatmoko, 2007).
Definisi politisi di republik ini patut diklarifikasi. Politisi sebenarnya bukan anggota partai, pemilik uang, atau tokoh populer. Politisi seharusnya mengandung dua makna pokok. Seorang politisi adalah sosok yang memiliki kemampuan membaca dan menangkap aspirasi masyarakat tanpa terbuai viralisme atau jualan media (Laclau, dkk., 2000). Jika kemungkinan pertama tidak terjadi, seorang politisi seharusnya mampu menciptakan discourse yang menyingkapkan kebutuhan objektif masyarakat luas dan menggiring masyarakat untuk menyadari, berpartisipasi dalam discourse, dan turut menyatakan persetujuan (Laclau, 2005).
Dari tiga nama dengan peluang tinggi untuk dicapreskan, hanya dua tokoh yang merupakan kader partai. Ini artinya, rerata parpol di Indonesia gagal mengorbitkan pemimpin yang lahir dari rahim kaderisasi partai. Ideologi dan mesin kaderisasi tidak bergerak atau karat atau tidak tahu arah sehingga dibutakan oleh popularitas individual. Padahal popularitas tidak simetris dengan kualitas.
Hanya Gerindra yang mencalonkan ketua umum sebagai calon presiden. Padahal ketum parpol adalah tokoh yang dipercayai kader. Dengan demikian kelihatan partai-partai gagal membaca kehendak umum masyarakat. Terbukti, ketua partai bukan sosok yang laris di masyarakat. Maka, kriteria pemilihan ketua partai sebenarnya bukan merepresentasi aspirasi rakyat, melainkan siapa yang memiliki ‘kantong tebal’. Oligarki di republik ini rupanya lebih bertumbuh subur pada era reformasi.