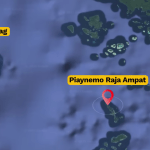Kebijakan publik bukan sekadar aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi merupakan instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan, menyejahterakan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan sosial. Menurut para pakar kebijakan publik dan pengamat politik, kebijakan yang baik harus berbasis bukti, partisipatif, serta mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Namun, realitas politik seringkali membuat kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan kajian akademis yang matang.
Menurut Thomas Dye, seorang pakar kebijakan publik, menggarisbawahi kebijakan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan bukan hanya soal tindakan aktif, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu isu.
Dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan yang seharusnya berbasis data dan kebutuhan masyarakat, tetapi justru lahir dari tekanan politik atau kepentingan ekonomi elite. Pengamat politik seperti Rocky Gerung dan Burhanuddin Muhtadi sering menyoroti kebijakan dibuat berdasarkan kompromi politik alih-alih analisis ilmiah yang kuat.
Pada kasus kebijakan di Indonesia, seringkali kebijakan diterapkan dengan terburu-buru dan terkesan tidak memiliki pertimbangan yang matang. Beberapa kasus seperti omnibus law, peningkatan tarif pajak, pemotongan anggaran besar-besaran dalam tubuh kementerian, dan kebijakan distribusi gas elpiji 3kg, telah menjadi contoh penerapan kebijakan yang kurang perhitungan dan beresiko merugikan kelompok rentan seperti perempuan.
Penerapan kebijakan di Indonesia seringkali berpedoman pada viral-based policy atau lebih populer lagi dikenal dengan istilah ‘kebijakan cek ombak’. Pendekatan kebijakan semacam ini, seakan-akan mengesampingkan pendapat publik dan analisis ilmiah sebagai komponen penting dalam sebuah perencanaan kebijakan.
Salah satu pendekatan yang disarankan oleh para pakar adalah kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, di mana keputusan dibuat berdasarkan data, penelitian akademik, dan evaluasi kebijakan terdahulu. Selain berbasis bukti, kebijakan yang efektif juga harus melibatkan partisipasi publik.
Jurgen Habermas, seorang filsuf politik, berpendapat bahwa demokrasi deliberatif adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang adil. Artinya, kebijakan harus dirumuskan dengan mendengar berbagai perspektif masyarakat, bukan hanya keputusan sepihak dari elite politik. Di Indonesia, proses ini masih menjadi tantangan karena seringkali kebijakan dibuat tanpa konsultasi yang cukup dengan masyarakat terdampak.
Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya soal aturan yang dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, diawasi, dan dievaluasi. Menurut Daron Acemoglu, ekonomi politik dalam bukunya Why Nations Fail, kebijakan yang gagal biasanya disebabkan oleh institusi yang lemah dan tidak adanya mekanisme check and balance yang efektif. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya mampu menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data, inklusif, dan transparan, bukan sekadar kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak. Jika kebijakan terus dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek dan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi beban sosial di masa depan dan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diterapkan.