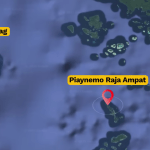Demokrasi nihil oposisi bak sayur tanpa garam. Ungkapan yang pas untuk menggambarkan kualitas kebijakan publik di Indonesia yang lahir ketika regresi demokrasi. Praktik berdemokrasi masa kontemporer yang tengah kehilangan marwah esensialnya.
Bagaimana tidak, setelah berakhirnya hiruk-pikuk tahapan pemilihan presiden hingga pelantikan presiden terpilih sejak Oktober 2024 lalu, belum ada satu partai pun yang lantang berteriak, “kami memilih beroposisi”. Padahal, demokrasi ialah panggung orkestrasi politik yang harus ramai dengan perdebatan dan perspektif yang saling berlawanan, demi menghasilkan kebijakan publik yang bermakna.
Sejatinya, praktik demokrasi tanpa partai oposisi di Indonesia memang bukan hal yang baru. Terutama era pasca Orde Baru dan pemilihan presiden secara langsung pertama kali pada 2004. Salah satunya, peristiwa bergabungnya Partai Golkar, PAN, dan PPP ke koalisi periode pertama pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan rival pemilu dari ketiga partai tersebut pada saat itu (Alamsyah, 2014).
Namun, perjalanan demokrasi kita kian tampak mempertontonkan keenganan partai politik untuk membangun identitas sebagai partai oposisi. Terlihat dari bergabungnya Partai Gerindra dan ketua umumnya, Prabowo Subianto, ke koalisi pemerintahan Joko Widodo pada 2019.
Kemenangan koalisi keberlanjutan dalam wajah Prabowo-Gibran menampilan raut yang sama tentang rapuhnya keberadaan partai oposisi. Dibentuknya KIM Plus dalam wujud Kabinet Merah Putih merupakan bukti yang sulit dibantah. Termasuk, PDI-P sebagai partai yang digadang-gadang menjadi antitesis pasca rezim Jokowi, lebih memilih jalan kerja sama dengan koalisi pemerintah (Harbowo, 2025).
Gimik politik PDI-P justru menarasikan oposisi dan koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial ala Indonesia. Memilih bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowo, telah mengaburkan definisi partai oposisi dalam konteks yang lebih luas. Kecenderungan partai politik memilih antara koalisi dan oposisi bukan lagi produk yang otomatis timbul dalam demokrasi di Indonesia, melainkan pengaruh agenda presiden untuk memperluas kekuasaannya (Slater, 2018).
Maka, apa jadinya kebijakan publik yang lahir dari demokrasi tanpa oposisi? Ketiadaan wujud partai oposisi akan memperlemah proses pembentukan suatu kebijakan publik yang berkualitas sebagai produk politik. Akibatnya, kebijakan publik akan rawan menggunakan “kacamata kuda”. Sehingga, memperluas titik buta pada tahapan pembentukan kebijakan publik yang partisipatif.
Bias Kepentingan yang Memperlemah Sistem Merit
Alam demokrasi yang nihil partai oposisi akan cenderung mengedepankan kawan dan mengesampingkan kepentingan publik. Kajian lawas dari Schmidt (1996) menyoroti bahwa pemilihan dan hasil dari suatu kebijakan paling besar ditentukan oleh komposisi partai politik pembentuk pemerintah. Dalam kondisi ideal, beragamnya partai politik dalam pemerintahan akan memperkaya perspektif kebijakan publik.
Nahasnya, politik di Indonesia lebih dikuasai oleh diskursus transaksional dan berorientasi keuntungan sesaat. Oleh karena itu, partai politik yang pada akhirnya bergabung dalam pemerintahan tampil tanpa beda dengan partai politik lainnya. Eksis tanpa membawa aspirasi konstituennya. Para pihak yang berkuasa cenderung mengedepankan stabilitas politik dengan mengikuti satu kepentingan, alih-alih menghidupi kultur demokrasi yang sehat dengan perdebatan substantif.
Kebijakan publik sudah selayaknya dirumuskan oleh entitas yang memiliki kompetensi mumpuni dalam bidang terkait dan pihak yang berkepentingan langsung di dalam diskursusnya. Namun, koalisi yang tebal dengan banyak kepentingan partai politik dan harus disuapi, membuat pos-pos pejabat publik lebih dipenuhi dengan orang-orang dekat dan berjasa bagi kekuasaan, alih-alih sosok yang berkompeten.
Akibatnya, patronase dan kroni politik tumbuh subur bagai ilalang yang menghimpit ruang bagi sistem berbasis merit untuk bersemi. Akhirnya, kebijakan publik bisa saja kian dipertanyakan kredibilitas dan orientasinya.
Pemilu bagai Parodi
Jika akhirnya seluruh partai politik bergabung menjadi satu koalisi dengan pihak pemenang, maka pemilu tidak ada artinya. Dengan demikian, pemilu tidak lebih dari sekadar parodi elite yang sebetulnya mempertontonkan siapa yang berhak memperoleh bagian kue kekuasaan paling besar, bukan siapa yang rela berkorban demi kepentingan konstituennya.
Pesimisme Slater (2018) dan Gottlieb (2015) sangat mendasar terhadap pernyataan tersebut, bahwa demokrasi tanpa oposisi yang nyata setelah pemilu akan menghilangkan efek ancaman (deterrence effect). Publik kehilangan kesempatan untuk memberikan tekanan sanksi bagi pihak pemenang pemilu jika kelak mereka tidak bekerja baik dalam pemerintahan—yakni dengan cara tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.
Sudah sejak lama, aktivis dan pemikir pro-demokrasi mengkritik alpanya peran esensial oposisi di Indonesia. Adanya bias kepentingan, pelemahan sistem merit, dan pemilu yang dijalankan layaknya parodi, hendak menekankan bahwa partai politik oposisi yang nyata di alam demokrasi Indonesia penting adanya.
Sebab, narasi stabilitas politik dan politik gotong-royong yang bernuansa feodal seakan menjustifikasi dan menormalisasi nihilnya oposisi, tak selayaknya menjadi pertimbangan dalam diskusi-diskusi tentang kebijakan publik dalam sistem kenegaraan. Demokrasi sudah seharusnya riuh dan saling berdebat, sebagaimana esensi utama demokrasi yang bermakna.