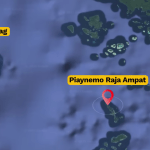This content has been archived. It may no longer be relevant
Negara demokrasi mengharuskan kontestasi untuk meraih kekuasaan. Genderang kompetisi hanya bisa ditabuhkan bila terdapat kelompok-kelompok yang siap berlaga. Bagaimanapun, perlombaan selalu memasang lawan dan kawan.
Kehadiran distingsi lawan dan kawan dalam politik sebenarnya lumrah, bukan masalah. Justru problematik ketika tidak menyiapkan kuota untuk lawan. Absennya lawan membunyikan alarm bahaya bagi demokrasi. Hanya negara otoriter-despotik yang menihilkan ruang untuk lawan politik.
Indonesia sejak awal kemerdekaan berkomitmen menganut sistem demokrasi. Sayangnya, komitmen itu diperam puluhan tahun, hingga era reformasi. Setelahnya, Indonesia dipandang sebagai negara yang sungguh demokratis, bahkan sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Kini telah lebih dari dua puluh tahun, sistem demokrasi dijalankan di Indonesia. Suatu usia yang tidak lagi muda jika dibandingkan dengan beberapa negara demokratis lainnya. Liku-liku pengalaman memperjuangkan demokrasi di negara kita patut diapresiasi. Kita pun memahami benar makna sebuah demokrasi dari tetesan darah para aktivis 90an.
Namun, kelihatan ada yang keliru dengan dekorasi pesta demokrasi kita akhir-akhir ini. Kekisruhan punggawa-punggawa partai politik secara terang-terangan menyudutkan lawan sebagai musuh. Untuk itu, kita perlu menarik garis demarkasi di antara lawan dan musuh.
Distingsi Lawan-Kawan
Distingsi lawan-kawan sebenarnya rambu-rambu lama di dalam akrobat politik. Namun, sebagai sebuah konsep politik, Carl Schmitt adalah pencetusnya dan Ernesto Laclau adalah ujung tombaknya. Menurut kedua ilmuwan politik ini, dikotomi lawan-kawan adalah konsep dan konstruksi politik. Ada empat alasan mendasar kemunculan distingsi kawan-lawan.
Pertama bersifat logis-analitis. Logika analitis berbeda dengan sintesis. Sintesis membutuhkan predikat ekternal untuk menjelaskan sebuah subjek. Contohnya, partai politik di Indonesia memiliki relawan yang bukan bawaan integral dari esensi sebuah partai. Relawan justru fenomena politik baru lantaran pori-pori demokrasi dalam partai politik tersumbat, tersedot jebakan oligarki, dan terlilit hal-hal administratif.
Adapun subjek analitis tidak membutuhkan unsur luar untuk menjelaskan dirinya. Sebagai contoh, partai memiliki ideolog sebagai jantung partai. Tanpa ideologi, sebuah partai tidak lebih dari komunitas. Di Indonesia, semua partai sudah pasti pancasilais. Tidak ada partai yang tidak pancasilais karena akan langsung digebuk sejak pendaftaran.
Sebab itu, keliru dari sudut logika analitis bila ada politisi tertentu yang mengaku partainya lebih pancasilais dari partai lain. Dari sudut logika analitis ini, konsep kawan-lawan adalah satu paketan. Mencabut yang satu, yang lain ikut terangkat.
Alasan logis-analitis lain ialah identitas hanya dapat dibentuk melalui konfrontasi dengan yang berbeda. Identitas kita hanya dapat didefinisikan dalam relasinya dengan lawan kita (Carl Smith, 1996). Warna partai merah hanya jelas bila ada partai lain yang berwarna hijau atau kuning.
Hal tersebut mengandaikan konsep identitas relasional-dialektis-rasional. Kita atau kawan hanya dapat berdiri dan tau apa yang harus dilakukan hanya jika adanya oposisi di seberang, mereka atau lawan (Kalyvas, 2008). Kawan-lawan adalah dua pasangan koeksistensial yang tidak dapat diceraikan di dalam politik demokrasi.
Kedua bersifat metafisis. Carl Schmitt menengarai, distingsi kawan-lawan lahir dari embedded-nya antagonisme di dalam realitas sosial. Antagonisme adalah sebuah konsep yang dipakai untuk fenomena negativitas sosial di dalam tradisi idealisme Jerman, romantisme, dan marxisme.
Bagi Laclau, antagonisme bukan sekadar data deskriptif-sosiologistik. Lebih dari itu ialah spot metafisis (Laclau, 2014). Antagonisme bukan kontradiksi konseptual atau oposisi riil Hegel, melainkan sebagai batas dari setiap objektivitas, yang disingkapkan sebagai objektifikasi yang parsial dan tak pasti.
Antagonisme adalah hakikat ontologis dari konflik, perjuangan, dan konfrontasi aktual (Marchart, 2018). Antagonisme hadir ketika relasi-relasi sosial objektif tidak dapat menjadi penuh dan selalu terbuka terhadap perubahan. Keniscayaan oposisi biner lawan dan kawan adalah konsekuensi dari antagonisme dalam realitas sosial (Laclau, 2005).
Ketiga, antagonisme memang dapat kita jumpai di dalam semua lini hidup seperti pada konflik, keretakan sosial lain, atau ritme sosial yang menuntut persaingan seperti pada pertandingan sepak bola. Praktek-praktek sosial ini selalu menghadirkan distingsi lawan-kawan. Meskipun begitu, antagonisme tidak langsung tampak pada mata fisik telanjang. Hanya mata nalar dapat meneropong gelagat antagonisme. Dibutuhkan abstraksi untuk menarik tirai yang menyembunyikan antagonisme.
Keempat, sebagai simpul politik, antagonisme direproduksi secara berkala melalui logika ekuivalensi dan pembedaan. Disparitas kawan-lawan adalah hasil formasi etikaic. Melalui logika ekuivalensi, barisan para kawan dirapatkan, perbedaan tujuan disatukan, di dalam oposisi langsung dengan lawan. Meskipun demikian, perseteruan ini hanya temporal karena tidak memiliki konten substansial atau referensi esensial. Logika pembedaan akan segera menggusur intimitas kamp kawan etika tujuan mereka sudah diraih.
Lawan Bukan Musuh
Meskipun distingsi kawan-lawan normatif di dalam realisme politik, pengabadian lawan akan menimbulkan riak-riak sosial. Memosisikan lawan politik pada status yang sama, mengabaikan potensi lawan split menjadi kawan, adalah upaya memeteraikan lawan sebagai musuh. Lawan politik bukan musuh. Keduanya berbeda secara ontologis dan logis.
Secara ontologis, partai A dapat menjadi lawan partai B pada Pilpres 2019, tetapi ia tidak lantas menjadi musuh bebuyutan pasca dansa politik 2019. Kepentingan politik selalu overlapping, sewaktu-waktu dapat bersua di tikungan yang sama. Karena itu, secara logis, semua lawan politik dapat menjajaki potensi menjadi lawan atau kawan.
Bahaya transformasi lawan menjadi musuh adalah absolutisasi konflik. Padahal, konflik kepentingan hanyalah selingan untuk menaikkan adrenalin. Sifat kepentingan memang abadi, tetapi isinya selalu tergerus konteks. Maka memaksa lawan politik menjadi musuh adalah bentuk kriminalisasi lawan. Tidak hanya kriminal, tetapi juga tidak etis, simpton ketidakdewasaan berpolitik, patologi demokrasi.
Mudah untuk membedakan kawan dan lawan. Yang sulit adalah menarik garis demarkasi di antara lawan dan musuh. Menjelang Pilpres 2024, setiap elit politik sebaiknya sesering mungkin mendengungkan perbedaan mendasar antara lawan dan musuh. Etika politik hanya akan menjadi bualan politisi jika tidak berniat dan mampu menghilangkan libido memusuhkan lawan.