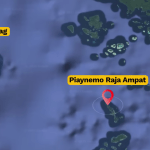Menjelang pembukaan tahun ajaran baru, admisi berbagai perguruan tinggi di tanah air riuh menjaring mahasiswa baru. Aneka tawaran program unggulan, akreditasi, hingga beasiswa diobral. Spanduk, papan reklame, bahkan iklan besar-besaran di media cetak dan daring berhamburan di berbagai sudut. Sayangnya, penentuan terakhir selalu berada pada satu kriteria: kemampuan akademik.
Kualifikasi di atas dianggap sebagai sensor pamungkas berbasis sistem meritokrasi (merit system) untuk menentukan seseorang layak berada dalam gelanggang para sarjana. Benarkah prinsip meritokrasi tepat untuk dijadikan rambu-rambu seleksi untuk berkuliah?
Prinsip Meritokrasi
Sistem meritokrasi melekat di dalam demokrasi karena dipandang sebagai artikulasi asas kebebasan dan kesetaraan. Di Amerika, Inggris, dan beberapa negara lainnya, prinsip meritokrasi tidak hanya dipakai di perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga diaplikasikan di dalam pelayanan publik (Juillet and Rasmussen, 2008: 189) hingga dunia pendidikan.
Belakangan penerapan sistem meritokrasi disadari justru mengkaratkan demokrasi dari dalam sehingga terjadi krisis dalam berbagai sektor. Beberapa HR eksekutif berpendapat, sistem merit tidak lagi relevan dengan manajemen publik kontemporer. Meritokrasi rawan manipulasi politik karena dipakai untuk mengikat loyalitas bawahan terhadap atasan sehingga malah membatasi seseorang untuk mengembangkan performa dan efisiensi kerjanya (Bowman and West, 2007).
Prinsip meritokrasi adalah “… penghargaan sebanding dengan prestasi dan usaha” (Ryan, 2011). Meritokrasi mendorong pencapaian efisiensi manajerial yang lebih besar (Juillet and Rasmussen, 2008). Prinsip meritokrasi bernas karena dua alasan: efisiensi dan fairness.
Di dalam norma meritokrasi, semua dan setiap individu sudah mendapatkan kesempatan yang sama, maka kesuksesan berada pada tangan setiap orang. Kerja keras menentukan keberhasilan. Karena itu, “… kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan” (J. Sandel, 2020). Setiap orang layak mendapatkan apapun selaras dengan kerja kerasnya.
Kekeliruan Meritokrasi
Penerapan sistem seleksi by merit ditimbang adil dan tepat karena tiga alasan utama: (1) untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi dan pencapaian pendidikan, (2) untuk mendorong dan menghargai prestasi akademik, dan (3) untuk menahan ‘brain drain’ siswa berprestasi ke perguruan tinggi (Heller, 2002).
Ketiga alasan di atas rupanya tidak dapat menampik fakta bahwa pola meritokrasi dalam dunia pendidikan justru menimbulkan ketidakadilan. Alih-alih menciptakan kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan untuk semua orang, lembaga pendidikan justru ikut mereproduksi kesenjangan sosial (Haryatmoko, 2010).
Perekrutan admisi berbasis prinsip meritokrasi yang dipersempit dengan pencapaian akademik dan potensi akademik semata justru menutup mata terhadap konteks seleksi yang lebih luas. Padahal kemampuan dan kualitas dinilai secara subjektif dan dikonstruksi secara sosial sebagaimana pernah dikatakan sejarawan Howard Wechsler, “Esensi admisi selektif adalah keputusan subjektif dari pejabat admisinya” (R. Posselt, 2016).
Kesalahan sistem meritokrasi terletak pada asumsi dasar bahwa semua orang memiliki kesetaraan kesempatan, sehingga pemenang bergantung pada usaha individu. Padahal, de facto tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang setara. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tinggal di tempat terpencil yang buruk infrastrukturnya mustahil memiliki akses untuk belajar di sekolah berkualitas dan kampus ternama seperti UGM dan UI.
Bahkan untuk bermimpi menjadi orang bergelar sarjana pun tidak, lantaran imajinasi dikonstruksi secara sosial. Maka, alih-alih membantu masyarakat mencapai kesejahteraan umum, meritokrasi hanya menciptakan siapa menang (winners) dan siapa kalah (losers). Yang bekerja keras layak menang. Yang kalah layak menahan malu (J. Sandel, 2020: 21-34).
Karena itu, seharusnya seleksi masuk perguruan tinggi didasarkan kesetaraan situasi (equality of situation). Kesetaraan situasi bukan konsep baru. Embrionya sudah disemai Aristoteles sejak era Yunani kuno dengan konsep equity: mendekati masalah dengan kriteria kepantasan atau adil sesuai partikularitas kasus, bukan prinsip kesetaraan keadilan yang menyamaratakan semua konteks hidup dan kebutuhan setiap orang (Aristotle, Nichomachean Ethics V).
Kesetaraan situasi menyasar kondisi riil setiap orang, terutama menawarkan bantuan untuk kelompok atau individu yang termarjinalisasi secara struktural. Kesetaraan situasi berkonsentrasi pada pluralitas kebutuhan setiap individu. Siswa yang lahir di kampung dan daerah tertinggal berbeda kebutuhan dengan siswa yang lahir di perkotaan dan daerah maju. Maka mereka pantas dibantu sesuai keluhan situasi mereka (J. Sandel, 2020).
Keinsafan atas ketidaksetaraan setiap individu dalam mengakses sumber daya-sumber daya justru akan melahirkan kerendahan hati sebagai kebajikan sipil dan tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Kerendahan hati timbul bila setiap orang memahami kesuksesannya bukan karena jerih payahnya atau talenta, melainkan faktor keberuntungan (J. Sandel, 2020).
Pendekatan berbasis kesetaraan kesempatan akan mendorong pelajar yang sukses bertanggung jawab untuk membantu sesamanya yang masih terbengkalai di belakang. Ia sadar bahwa tersendat-sendat hidup sesamanya bukan kutukan atau takdir, melainkan ganjalan struktural yang memangkas jalan hidup seseorang menuju paripurna kapabilitasnya.